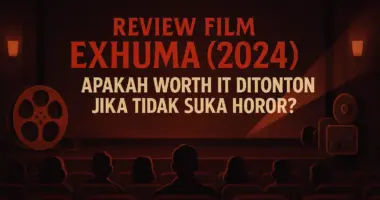Ridley Scott memboyong Napoleon Bonaparte ke layar lebar dalam epik berdurasi dua setengah jam yang langsung jadi sasaran kritik sejarawan. Bukan pertanyaan apakah film ini akurat—tapi seberapa jauh Scott rela melanggar fakta demi drama. Dan jawabannya? Cukup jauh untuk bikin akademisi berkeringat, tapi cukup dekat untuk menghibur.
Napoleon di Layar Lebar: Epik atau Epic Fail?
Film ini bukan biografi linear. Scott dan penulis naskah David Scarpa lebih tertarik pada psikologi sang kaisar daripada kurikulum sejarah. Hasilnya? Sebuah mahakarya visual yang ambisius tapi selektif soal fakta.
Timeline dipadatkan. Peristiwa yang terjadi bertahun-tahun digabung jadi satu adegan. Lokasi direlokasi. Karakter komposit muncul di mana-mana. Tapi semua ini dilakukan dengan sengaja, bukan karena kelalaian.
Scott pernah bilang, “Ini film, bukan kuliah sejarah.” Dan itu terasa di setiap frame. Dia lebih peduli pada emosi daripada akurasi kronologis.

Joaquin Phoenix: Kaisar yang Terlalu Manusiawi
Phoenix mainkan Napoleon sebagai sosial awkward, posesif, dan terobsesi Josephine. Bukan sosar heroik atau jenius strategis. Ini Napoleon yang gelisah, sering terdiam di pojok ruangan, lalu tiba-tiba meledak.
Pilihan akting ini kontroversial. Beberapa bilang “tidak meyakinkan” sebagai komandan hebat. Tapi justru di sinia letak kebriliannya. Phoenix menolak klise “pemimpin karismatik” dan tawarkan versi yang lebih gelap, lebih labil.
Dialognya minimal. Ekspresinya yang bercerita. Dalam satu adegan pesta, dia cuma duduk sambil memandangi Josephine—dan semua kegilaannya tercermin dari tatapan itu.
Josephine: Fokus Sejati Film Ini
Kalau ada yang akurat, itu adalah peran Vanessa Kirby sebagai Josephine. Bukan akurasi historis, tapi akurasi emosional. Josephine di sini bukan cuma istri, tapi obsesi sentral Napoleon.
Kimia antara Phoenix dan Kirby adalah nyeri dan magnetik. Hubungan mereka toxic, bergantung, tapi tak terpisahkan. Scott habiskan banyak waktu di kamar tidur mereka daripada di medan perang.
Ini pilihan narratif yang berani. Film ini sebenarnya love story yang diselubungi epik perang. Dan Kirby mencuri setiap adegan dengan charm dan kepedihan yang halus.
Pertempuran Megah, Fakta Ragu-ragu
Bagian visual memang tidak main-main. Pertempuran Austerlitz direkayasa dengan detail brutal—sampai tentara jatuh ke danau beku. Tapi sejarawan protes: “Itu nggak pernah terjadi!” Scott jawab: “Tapi kan keren.”
Waterloo juga diperdebatkan. Formasi, strategi, bahwa cuaca—semua dipoles demi dramatisasi. Scott pakai drone shot dan CGI untuk menciptakan immersive chaos yang bikin penonton merasa ada di tengah-tengahnya.
Daftar perubahan signifikan:
- Usia karakter: Napoleon digambarkan lebih tua di awal karir
- Timeline: Beberapa kampanye digabung atau dipersingkat
- Dialog: Banyak ucapan ikonik yang dimodifikasi atau diciptakan
- Setting: Beberapa lokasi penting dipindah demi visual yang lebih kuat

Creative License vs Fakta Sejarah
Masalahnya bukan sekadar “benar atau salah.” Ini soal tujuan. Scott nggak bikin dokumenter BBC. Dia bikin drama tentang obsesi, kekuasaan, dan kehilangan.
Sejarawan Andrew Roberts menyebut film ini “insult to history.” Tapi sutradara seperti Scott selalu punya alasan: fakta seringkali membosankan. Realitas perang penuh dengan waktu tunggu, kebingungan, dan birokrasi.
Film harus punya busur naratif yang jelas. Scott pilih busur personal—Napoleon sebagai pria yang terobsesi—dan gunakan perang hanya sebagai latar.
Contoh Konkret Modifikasi
Salah satu adegan paling ikonik adalah kronometer di Austerlitz. Napoleon pakai jam untuk sinkronkan serangan. Visualnya keren, tapi sejarawan bilang itu oversimplifikasi besar-besaran. Strategi sebenarnya jauh lebih kompleks.
Tapi Scott nggak peduli. Dia mau visual metaphor yang mudah dipahami: Napoleon sebagai pria yang mengendalikan waktu itu sendiri.
Apakah Film Ini “Salah”?
Tergantung ekspektasi. Mau dokumenter? Nonton History Channel. Mau drama epik dengan karakter kompleks? Ini filmmu.
Akurasi sejarah: 40-50% untuk detail besar, 20% untuk nuansa. Tapi akurasi emosional? Mungkin 80%. Scott berhasil tangkap esensi obsesif Napoleon, meski dengan cara yang fiksi.
Film ini bukan tentang apa yang benar terjadi, tapi tentang bagaimana perasaan seseorang dengan kekuasaan mutlak yang tetap manusia. Dan di sini, Scott menang.
Pilihan akhirnya di tangan penonton. Bisa marah soal fakta, atau bisa terima ini sebagai interpretasi artistik. Sama seperti Shakespeare punya versi Richard III yang jauh dari fakta, Scott punya versi Napoleon-nya sendiri.
Yang pasti, diskusi soal akurasi justru bikin film ini lebih relevan. Setidaknya Scott berani ambil risiko, bukan main aman dengan biografi steril.
Kesimpulan: Tonton untuk Spektakel, Bukan untuk Ujian
Napoleon adalah film yang provokatif—bukan karena kontennya, tapi karena pendekatannya. Scott tegaskan garis antara sejarah dan hiburan, dan undang penonton untuk diskusi.
Visualnya memukau, aktingnya kontroversial tapi memorable, dan narasinya fokus. Tapi yang paling penting: ini film yang menghibur. Dan di dunia biopik yang seringkali membosankan, itu pencapaian tersendiri.
Jadi, apakah akurat? Tidak. Apakah layak ditonton? Sangat—asal kamu siap melupakan buku sejarah sebentar dan terima drama obsesi Ridley Scott.